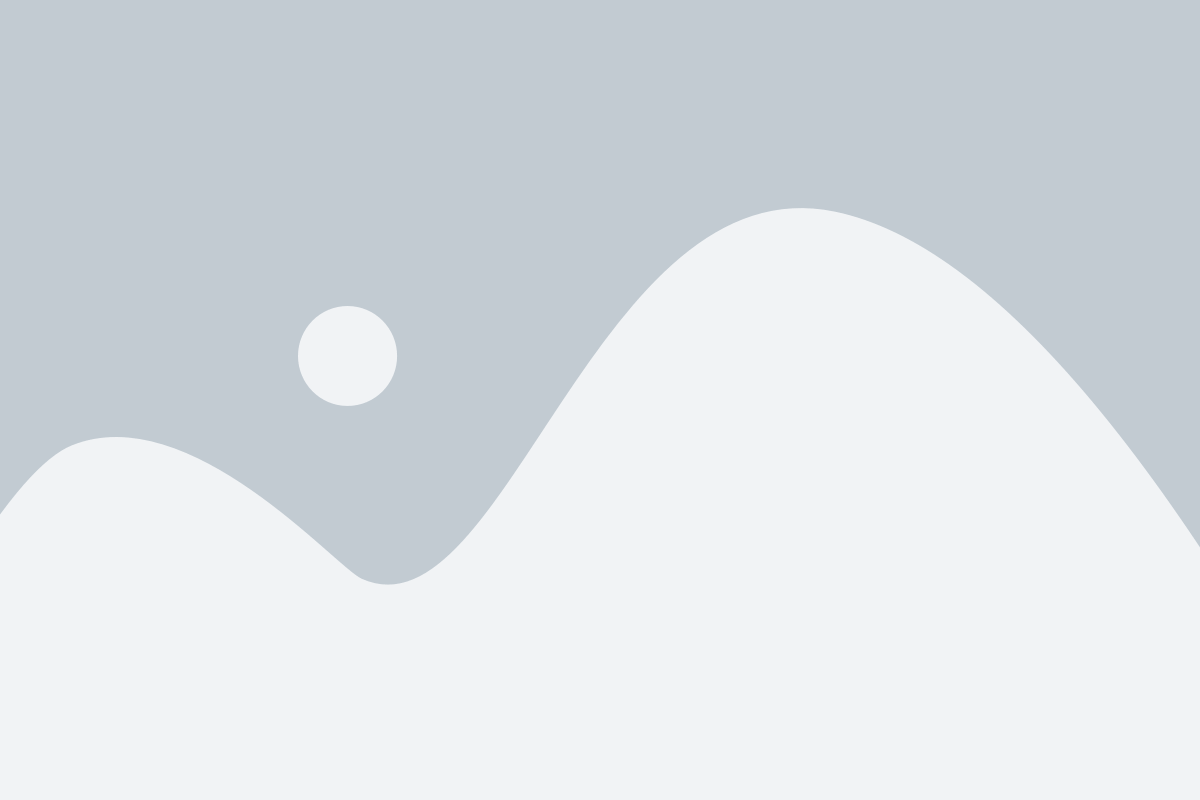Pati – Salah satu nasihat ulama yang paling saya ingat sejauh ini berasal dari Imam Ghazali: jika kamu bukan anak seorang raja, bukan pula anak seorang ulama besar, maka menulislah.
Ada beberapa alasan mengapa kutipan ini amat membekas di kepala. Pertama, Al Ghazali menyampaikan realitas tentang “nama” manusia di masyarakat bagaimana posisi mereka dalam tatanan sosial. Kedua, ia menggunakan contoh “raja” dan “ulama”, yang berimplikasi pada keterkaitan dua aspek sekaligus, yakni umum dan agama. Ketiga, saya memang hobi menulis; ucapan Al Ghazali adalah penguat semangat.
Anda bisa dengan mudah menemukan kutipan-kutipan lain, entah dari tokoh besar luar maupun dalam negeri, dan semuanya punya ruang untuk membuat sesuatu di dalam hati kita semakin bulat. Butuh satu buku agar kita jatuh cinta pada membaca; satu nasihat dari siapa pun dapat membawa kita pada titik yang lebih baik dalam konteks ini: menulis.
Dari dulu saya menganggap menulis menandai keterampilan dasar “akhir” dari manusia. Kita telah mendengar sejak lahir, berbicara tak berapa lama kemudian, lalu membaca, dan menulis berada paling akhir. Sering sekali saya katakan pada kawan-kawan: jika kamu ingin mengetahui kapasitas seseorang, lihatlah dari tulisannya.
Saya tak hendak mengatakan bahwa orang yang tidak atau tidak bisa menulis itu buruk belaka. Tidak. Yang hendak saya tekankan di sini: menulis adalah usaha untuk menambah pengetahuan, menciptakan kreativitas dan kebijaksanaan pada waktu yang sama.
Ketika kita menulis, kita membutuhkan banyak waktu: kita menyusun kata per kata, memilih gagasan yang tepat dengan data-data sesuai, menyuntingnya baik secara kebahasaan maupun substansi, baru kemudian menyerahkannya kepada seseorang atau publik. Model inilah yang tidak diakomodasi ketika kita berbicara biasa. Kita cenderung tak punya waktu banyak untuk berpikir dan akibatnya, apa pun yang diucapkan lebih rawan keliru dari pada saat kita menulis.
Tulisan memfasilitasi siapa pun untuk menggali seberapa dalam ide yang dimiliki, mempertanyakan ulang kesahihan, dan menemukan bentuk penyampaian macam apa yang paling pas. Saya kira inilah mengapa tokoh-tokoh terkenal dan penting selalu membukukan gagasannya, betapapun kini teknologi memungkinkan kita merevisi berulang kali jika misalnya, ada kesalahan dalam take video.
Ibnu Qosim Al Ghazi telah menuntun begitu banyak orang untuk belajar Fiqih dalam Fathul Qarib; Imam Syafi’i menuliskan Ushul Fiqih secara komprehensif di Ar Risalah; dan KH. Hasyim Asy’ari membikin nama negeri ini harum sekali dengan Adab al Alim wa al Mutaalim dan Annur al Mubin fi Mahabatti Sayyid al Mursalin. Ini hanya sedikit contoh dari begitu banyak ulama kita yang mengabadikan gagasan-gagasannya dalam tulisan. Dan kita sama-sama tahu: semua (nama) itu abadi.
Namun, apakah menulis hanya soal menjadi terkenal dan abadi?
Saya rasa tidak. Ruh lain dalam menulis adalah bagaimana kita terus mempertanyakan diri sendiri, menimbang-nimbang apa saja hal yang kita tahu dan miliki. Menulis tak pernah sama dengan mengigau. Menulis adalah merangkai satu demi satu premis, mengurutkan logika, menempatkan bahasa dalam potensi terbaiknya sesuai apa yang ingin disampaikan.
Dalam proses pembelajaran, prinsip inilah yang sebetulnya juga membentuk karakter civitas academica yang kuat. Guru dan murid sama-sama perlu memegang kuat visi untuk terus belajar dan menyusun tiap keping menjadi satu pandangan yang utuh dan kokoh. Salah satu hal penting dalam menulis adalah kesediaan mencari informasi belajar pun begitu.
Tidak ada satu pun penulis yang berangkat dari kekosongan. Para pembelajar sejati takkan pernah merasa puas dengan ilmu yang dipunyai.
Saya kira, kualitas iklim suatu institusi pendidikan bisa dilihat dari sana: apakah guru-siswanya menulis? Apakah sekolah tersebut mengakomodasi pelatihan-pelatihan untuk menulis?
Mari kita lihat pada diri sendiri. (Miftahur Rohim, S.S./ Humas MTs Salafiyah Pati)
- Editor: athi’mufida/qq